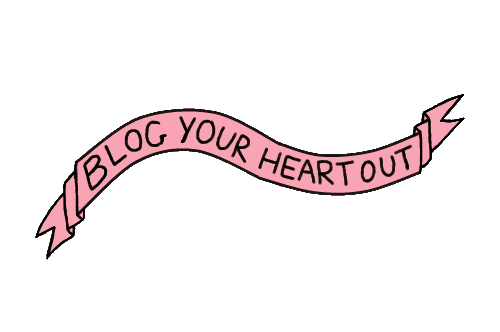17 March 2012 | 12:36 PM | 0 Sweet Hearts

Dunia adalah sebuah jenaka bagi orang bodoh!”
Tentu sahaja tergamam aku dibuatnya. Apa tidaknya, daripada tampangnya yang mirip gadis jalanan itu, terpancut kata-kata yang pernah diselipkan oleh Shakespeare menerusi salah sebuah dramanya.
Tentu sahaja tergamam aku dibuatnya. Apa tidaknya, daripada tampangnya yang mirip gadis jalanan itu, terpancut kata-kata yang pernah diselipkan oleh Shakespeare menerusi salah sebuah dramanya.
Kemudian aku menggeleng-geleng lesu, tersenyum lirih.
“Mengapa kau tersenyum?” sergahnya. “Kau tahu, kisah hidupku ini tragik daripada kisah Macbeth.”
“Mengapa kau tersenyum?” sergahnya. “Kau tahu, kisah hidupku ini tragik daripada kisah Macbeth.”

Sekali lagi aku tergamam, menancapkan sorot mata tepat-tepat ke wajah yang diselubungi seribu tanda tanya yang sukar untuk kutebak.
“Apa yang kaucari?” tanyaku sambil menggaru-garu dagu yang tidak gatal. Dia mendengus, mengetap-getap bibir.
“Sebuah rumah yang berjiwa.”
“Maksudmu?”
“Sudah sebulan aku meninggalkan rumah.”
“Hmmm…”
“Selama ini aku merasakan diriku lahir tanpa ayah dan ibu.”
“Kau masih punya orang tua?”
“Ya, tapi…”
“Tapi apa?”
“Mereka dengan hal masing-masing.”
“Maksudmu?”
“Ayahku seorang pemabuk.”
“Ibumu?”
“Gila… gila judi. Saban hari dia menjadi hamba jackpot dan pada hujung minggu sibuk dengan pertaruhan lumba kuda.”
“Kau punya adik-beradik?” Dia menggeleng keras.
“Kau tidak bersekolah?”
“Alam persekolahan sudah lama aku tinggalkan. Kau tahu, sebenarnya aku menyayangi alam persekolahan. Tapi… tapi aku terpaksa meninggalkan segala-galanya itu.”
“Sebuah rumah yang berjiwa.”
“Maksudmu?”
“Sudah sebulan aku meninggalkan rumah.”
“Hmmm…”
“Selama ini aku merasakan diriku lahir tanpa ayah dan ibu.”
“Kau masih punya orang tua?”
“Ya, tapi…”
“Tapi apa?”
“Mereka dengan hal masing-masing.”
“Maksudmu?”
“Ayahku seorang pemabuk.”
“Ibumu?”
“Gila… gila judi. Saban hari dia menjadi hamba jackpot dan pada hujung minggu sibuk dengan pertaruhan lumba kuda.”
“Kau punya adik-beradik?” Dia menggeleng keras.
“Kau tidak bersekolah?”
“Alam persekolahan sudah lama aku tinggalkan. Kau tahu, sebenarnya aku menyayangi alam persekolahan. Tapi… tapi aku terpaksa meninggalkan segala-galanya itu.”
Aku diam, mendenting-dentingkan syiling di dalam saku seluarku.
“Berikan aku beberapa keping syilingmu itu, aku akan membeli sebuah rumah!”
Lagi tersentak aku dibuatnya. Apakah dia boleh kusamakan dengan manusia gila. Husy! Dengan beberapa keping syiling, dia akan membeli sebuah rumah?
“Jangan tersentak. Itulah sahaja harapan yang tinggal dalam diriku ini. Mungkin jenaka sifatnya, tapi itulah hakikat yang sebenarnya. Aku… aku sudah tidak sanggup lagi menghadap sebarang tragedi. Seboleh-bolehnya aku ingin menjadi seperti watak lawak dalam A Midsummer Night’s Dream pula.”
Lagi tersentak aku dibuatnya. Apakah dia boleh kusamakan dengan manusia gila. Husy! Dengan beberapa keping syiling, dia akan membeli sebuah rumah?
“Jangan tersentak. Itulah sahaja harapan yang tinggal dalam diriku ini. Mungkin jenaka sifatnya, tapi itulah hakikat yang sebenarnya. Aku… aku sudah tidak sanggup lagi menghadap sebarang tragedi. Seboleh-bolehnya aku ingin menjadi seperti watak lawak dalam A Midsummer Night’s Dream pula.”
“Kau… kau tidak habis-habis bercakap tentang Shakespeare…” Dia tersenyum lirih, menggeleng-geleng lesu.
“Sejak lama aku bercita-cita untuk menjadi pelakon teater. Dan semasa zaman persekolahan dahulu, aku pernah juga menonton pementasan drama Shakespeare, juga menonton dramanya yang difilemkan.
“Jika kau juga peminat setia Shakespeare, kau lihatlah betapa hebatnya lakonan Kenneth Branagh yang sekali gus mengarah Hamlet. Tapi sayang,tiada siapa yang mendorong aku untuk ke arah itu, lebih-lebih lagi ayah dan ibuku.”
“Tentu… tentu kau punya bakat yang besar.”
Dia tersenyum lagi, menancapkan sorot matanya ke wajahku. “Tapi segala-galanya itu sudah terbuang jauh. Kini segala-galanya kosong. Kosong, kau tahu?”
Dia tersenyum lagi, menancapkan sorot matanya ke wajahku. “Tapi segala-galanya itu sudah terbuang jauh. Kini segala-galanya kosong. Kosong, kau tahu?”
Aku diam saja.
“Tolong berikan syilingmu itu. Tolong…” Ku dentingkan beberapa keping syiling ke telapak tangan kanannya.
“Terima kasih. Aku akan membeli sebuah rumah…”
“Tolong berikan syilingmu itu. Tolong…” Ku dentingkan beberapa keping syiling ke telapak tangan kanannya.
“Terima kasih. Aku akan membeli sebuah rumah…”
AKU sendiri tidak tahu bagaimana aku boleh tertarik mendekatinya. Suatu pagi, turun daripada tube di stesen Tottenham Court Road, antara penumpang yang sesak menuju pintu keluar, kulihat seorang gadis yang kukira masih belasan tahun, duduk di salah satu pojok, membentang sehelai kertas yang penuh bertampal wajah-wajah Shakespeare. Di atas kertas itu terdapat beberapa keping syiling.
Kurang lebih tiga meter dari tempat gadis itu duduk, seorang pemuda Negro memetikgitar sambil mengalunkan sebuah lagu berentak raggae, kukira lagu Bob Marley.
Setidak-tidaknya fesyen rambut dan topinya itu menyerupai gaya mendiang “raja raggae” itu. Namun tumpuanku tetap terpaku pada gadis yang duduk memaut lutut sambil merenung gambar-gambar Shakespeare di hadapannya.
“Siapa namamu?” tegurku sambil bercangkung. Dia mendongak, terkebil-kebil menatap mukaku.
“Siapa namamu?” ulangku.
“Lucie …”
“Siapa namamu?” ulangku.
“Lucie …”
Apa yang kaucari, Lucie? Di tengah-tengah kesibukan manusia yang lalu-lalang itu, kau duduk memaut lutut, menanti dentingan demi dentingan syiling sambil menatap gambar-gambar Shakespeare yang semakin lusuh dimakan hari.
Sepatutnya kau berada di sekolah sekarang. Tapi seperti yang telah kau atakan, segala-galanya itu telah kosong. Bolong belaka.
Barangkali ayahmu masih di bar, minum dan mabuk sepuas-puasnya. Dan ibumu pula seharian menghadap mesin jackpot, atau ya, ya, hari ini hari Sabtu, tentu ibumu di gelanggang lumba kuda, mempertaruhkan nasibnya pada kuda-kuda dan para jockey yang sama sekali tidak mengenalinya.
Dan kau pula masih di bawah terowong bawah tanah ini, menatap wajah Shakespeare atau sesekali mendengar rakanmu si Negro itu mengalunkan lagu-lagu Bob Marley, yang dibauri ngauman tube yang tidak lelah-lelah menelan penumpang saban hari dan malam.
“Dunia adalah sebuah jenaka bagi orang bodoh!” Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan menerusi ungkapan yang kau pinjam daripada Shakespeare itu.
Atau kata-kata itu hanya untuk memancing manusia yang lalu-lalang di hadapanmu agar berhenti dan mendentingkan syiling di atas kertas yang kau bentangkan itu.
Maafkan aku jika telahanku itu tersasar jauh. Dan maaf sekali lagi, itulah pertama kali aku terjumpa denganmu sesudah beberapa minggu aku berulang alik dari tempat tinggalku di timur kota London, ke stesen tube Tottenham Court Road, sebelum berjalan kaki ke Russel Square.
Sebelum ini kau di mana? Membentangkan kertas yang bertampal gambar-gambar Shakespeare itu di stesen tube yang lain?
“Aku impikan sebuah rumah yang berjiwa.”
Ah! Sebuah ungkapan yang menceritakan segala-galanya, Lucie. Keadaan memaksa kau menjadi pengemis – bukan mengemis syiling tentunya. Lebih daripada itu, Lucie. Tapi maaf, hanya beberapa keping syiling itu yang dapat kudentingkan untukmu.
Ah! Sebuah ungkapan yang menceritakan segala-galanya, Lucie. Keadaan memaksa kau menjadi pengemis – bukan mengemis syiling tentunya. Lebih daripada itu, Lucie. Tapi maaf, hanya beberapa keping syiling itu yang dapat kudentingkan untukmu.
“Berikan aku beberapa keping syilingmu itu, dan aku akan membeli sebuah rumah!”
Pada mulanya aku cuba tersenyum lebar-lebar mendengar kata-katamu itu, namun apabila memandang raut wajahnya yang tetap serius, hasratku itu terkubur begitu saja. Aku percaya ada sesuatu yang amat bermakna, meletus daripada bibirmu itu. Tapi aku sendiri tidak tahu apa makna sebenarnya.
Pada mulanya aku cuba tersenyum lebar-lebar mendengar kata-katamu itu, namun apabila memandang raut wajahnya yang tetap serius, hasratku itu terkubur begitu saja. Aku percaya ada sesuatu yang amat bermakna, meletus daripada bibirmu itu. Tapi aku sendiri tidak tahu apa makna sebenarnya.
“Dunia adalah sebuah jenaka bagi orang bodoh!”
Ah! Lagi-lagi ungkapan itu yang kaulafazkan…
HARI ketiga, kutemui lagi dia. Kali ini dia berdiri tegak sambil memegang sebuah buku. Tiada bentangan kertas yang bertampal gambar Shakespeare di hadapannya.
Ah! Lagi-lagi ungkapan itu yang kaulafazkan…
HARI ketiga, kutemui lagi dia. Kali ini dia berdiri tegak sambil memegang sebuah buku. Tiada bentangan kertas yang bertampal gambar Shakespeare di hadapannya.
“Kau membaca Othello?” tegurku.
“Ah! Kau lagi? Mengapa kau sibuk sangat mengganggu aku?”
“Maaf…”
“Kau tahu, hari ini aku menjadi Desdemona. Dan… dan kau bukannya Othello. Jangan ganggu aku. Sepanjang hari ini aku ingin menghafal dialog yang dituturkan oleh Desdemona. Pergi…Pergi…”
“Ah! Kau lagi? Mengapa kau sibuk sangat mengganggu aku?”
“Maaf…”
“Kau tahu, hari ini aku menjadi Desdemona. Dan… dan kau bukannya Othello. Jangan ganggu aku. Sepanjang hari ini aku ingin menghafal dialog yang dituturkan oleh Desdemona. Pergi…Pergi…”
Aku tidak berganjak.
“Kau ni siapa?” sergahnya.
“Manusia …”
“Ha… ha … barangkali kau ni gila. Lebih gila daripada Macbeth, si pemabuk darah itu.”
“Maaf. Aku bukan watak bikinan Shakespeare. Aku manusia yang tegak sebagai diriku sendiri.” Dia melongo, menjengilkan mata.
“Kau berdrama?”
“Tidak. Aku di dunia nyata sekarang. Kau yang berdrama.”
“Tidak ada bezanya…”
“Ada bezanya.”
“Ah! Aku kata tidak ada bezanya. Kau dengar, tak?”
“Aku mendengar sesuatu yang lain.”
“Sesuatu apa?”
“Sesuatu dari dalam dirimu.”
“Apa yang ada dalam diriku?”
“Kau jangan bertanya kepada aku. Tanyalah kepada dirimu sendiri.” “Ah! Kau memang gila. Gila…”
“Tidak ada manusia yang gila sebenarnya. Kegilaan itu hanya datang apabila manusia itu tidak dapat mengawal keadaan di dalam dan di luar dirinya. Kau juga tidak gila, cuma…”
“Kau ni siapa?” sergahnya.
“Manusia …”
“Ha… ha … barangkali kau ni gila. Lebih gila daripada Macbeth, si pemabuk darah itu.”
“Maaf. Aku bukan watak bikinan Shakespeare. Aku manusia yang tegak sebagai diriku sendiri.” Dia melongo, menjengilkan mata.
“Kau berdrama?”
“Tidak. Aku di dunia nyata sekarang. Kau yang berdrama.”
“Tidak ada bezanya…”
“Ada bezanya.”
“Ah! Aku kata tidak ada bezanya. Kau dengar, tak?”
“Aku mendengar sesuatu yang lain.”
“Sesuatu apa?”
“Sesuatu dari dalam dirimu.”
“Apa yang ada dalam diriku?”
“Kau jangan bertanya kepada aku. Tanyalah kepada dirimu sendiri.” “Ah! Kau memang gila. Gila…”
“Tidak ada manusia yang gila sebenarnya. Kegilaan itu hanya datang apabila manusia itu tidak dapat mengawal keadaan di dalam dan di luar dirinya. Kau juga tidak gila, cuma…”
“Cuma apa?” bentaknya.
“Kau cuba menjadikan dirimu gila di mata orang yang lalu-lalang di sini, bukan? Hakikatnya tidak begitu.” Dia tunduk merenung lantai.
“Kau cuba menjadikan dirimu gila di mata orang yang lalu-lalang di sini, bukan? Hakikatnya tidak begitu.” Dia tunduk merenung lantai.
“Maaf. Aku sudah terlambat, hanya beberapa minit lagi kuliahku akan bermula.”
“Kau belajar?”
“Ya, barangkali tentang sesuatu yang gila…” Dia terpaku, namun tangan kanannya masih erat menggenggam Othello.
“Mungkin esok kau boleh ceritakan kepadaku tentang Othello yang kau baca itu,” kataku sambil berlalu meninggalkannya.
“Hei! Dunia adalah sebuah jenaka bagi orang bodoh!” jeritnya kepadaku.
“Kau belajar?”
“Ya, barangkali tentang sesuatu yang gila…” Dia terpaku, namun tangan kanannya masih erat menggenggam Othello.
“Mungkin esok kau boleh ceritakan kepadaku tentang Othello yang kau baca itu,” kataku sambil berlalu meninggalkannya.
“Hei! Dunia adalah sebuah jenaka bagi orang bodoh!” jeritnya kepadaku.
Beberapa orang yang lalu-lalang di situ memandang ke arahku. Sesetengahnya mengomel sesama sendiri, tersenyum sinis, menjuihkan bibir.
Ah! Apalah yang hendak dimalukan. Mereka semua belum tentu orang yang tidak gila!
HARI keempat, dia tidak ada di situ lagi. Namun di pojok tempat dia duduk dan berdiri dua tiga hari lalu itu kutemui buku Othello. Sudah koyak-koyak. Dan di halaman pertama buku itu, kulihat bekas titisan darah. Sudah kering.
Tertulis namanya – Lucie alias Desdemona. Dan wajah Shakespeare yang tertera di kulit buku itu telah tertebuk kedua-dua belah matanya, dan di hujung bibirnya terlukis menyerupai taring dengan titis-titis darah. Di leher gambar Shakespeare itu pula tertulis Dracula. Apa yang kaucari, Lucie? Shakespeare sudah lama mati. Dan kau masih hidup lagi…

0 Sweet Hearts(s)